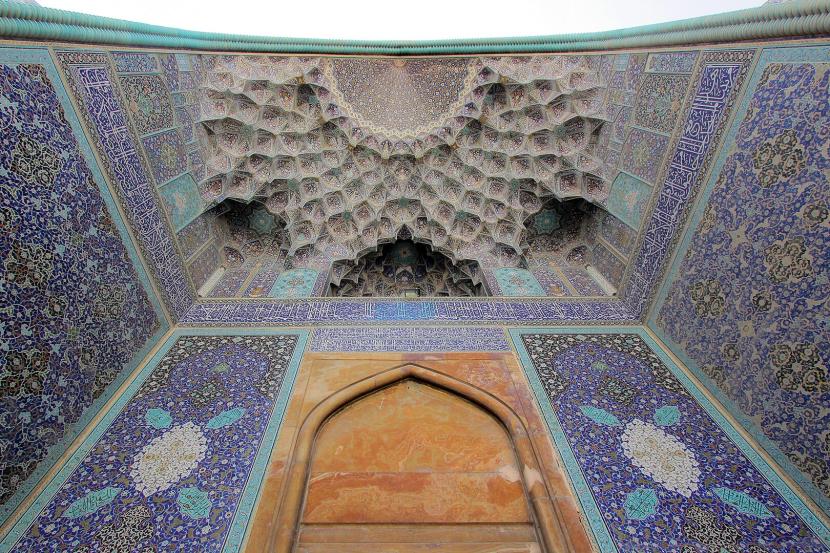Andinie Novia Sipayung
Andinie Novia Sipayung
Politik | 2025-10-17 00:26:34

Program Makanan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang menjadi tiket Indonesia menuju Generasi Emas 2045, kini berada di persimpangan jalan. Niat mulia untuk memutus rantai malnutrisi dan mencerdaskan anak bangsa justru berubah menjadi tragedi nasional. Alih-alih menambah energi, program ini justru menebar ancaman keracunan massal yang telah mengirim ribuan siswa ke rumah sakit di berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Sleman, hingga Lombok. Sebuah program triliunan rupiah yang seharusnya menjadi investasi masa depan kini justru mengancam nyawa generasi penerusnya sendiri.
Program MBG sejatinya bukanlah ide baru. Banyak negara telah membuktikan keefektifannya dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa, sekaligus menjadi garda terdepan melawan malnutrisi. Namun, penerapannya di Indonesia disebabkan oleh insiden keracunan yang masif. Data Kementerian Kesehatan per Oktober 2025 yang menyebutkan lebih dari 12.000 kasus keracunan sejak program ini digulirkan secara luas adalah lonceng peringatan yang memekakkan telinga. Pertanyaan mendasar pun muncul: di mana letak kesalahan program yang telah menelan anggaran negara begitu besar ini?
Penyelidikan polisi dan dinas kesehatan pada rentang Mei-September 2025 menunjuk pada satu tersangka utama: kebersihan pangan yang fatal pada tingkat implementasi. Ditemukannya mikroorganisme berbahaya seperti Salmonella dan E. coli pada sampel makanan menjadi bukti sahih adanya kejahatan. Dari sudut pandang ilmu pangan, ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum waktu dan suhu. Pangan yang dimasak dan dibiarkan terlalu lama dalam "Zona Bahaya" (rentang suhu 5°C hingga 60°C) akan berubah menjadi medium ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, mengubah hidangan bergizi menjadi bom waktu biologis. Laporan keracunan di Karanganyar dan Bogor (Mei 2025) mengonfirmasi praktik berbahaya ini, di mana makanan disiapkan jauh sebelum waktu makan, bahkan sejak malam sebelumnya.
Masalah ini semakin kompleks karena melibatkan dua titik kritis lainnya: kualitas bahan baku dan kompetensi petugas pengolah makanan. Pengawasan di hulu yang lemah membuat bahan baku yang tidak segar atau terkontaminasi lolos seleksi. Di hilir, para petugas—yang sebagian besar berasal dari UMKM lokal—sering kali abai terhadap standar higiene dasar seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, atau memastikan celemek kebersihan. Ironisnya, niat pemerintah memberdayakan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM justru menjadi bumerang karena tidak diimbangi dengan pelatihan dan pendampingan sanitasi yang memadai. Fokus pada penciptaan lapangan kerja seolah-olah tidak menjamin keselamatan pangan.
Kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan kenyataan di lapangan memperparah kondisi. Pelaksanaan diserahkan kepada ribuan Unit Pelayanan Penuh Gizi (SPPG) dengan kapasitas yang sangat bervariasi. Banyak dapur UMKM yang terlibat tidak memiliki fasilitas esensial seperti termometer, akses air bersih yang layak, atau tempat cuci tangan yang memadai. Norma ketat dari BPOM hanya menjadi macan kertas tanpa pengawasan dan penegakan yang konsisten. Bagaimana pelaku UMKM, yang mungkin memiliki keterbatasan pendidikan, dapat memahami konsep kontaminasi silang tanpa adanya pendampingan yang intensif?
Longgarnya pengawasan rutin oleh otoritas kesehatan setempat, seperti Puskesmas atau petugas sanitasi, menjadi pemantik utama dari bencana ini. Inspeksi mendadak atau pengujian sampel makanan secara acak seharusnya menjadi prosedur standar, bukan tindakan reaktif setelah korban jatuhan. Sikap ini menunjukkan bahwa keamanan pangan masih dianggap sebagai respon krisis, bukan investasi preventif.
Agar MBG tidak selamanya disebut sebagai "program berbahaya", reformasi sistem dan logistik harus segera dilakukan. Pertama, wajibkan "Lisensi Masak" bagi setiap petugas pengolah makanan. Lisensi ini hanya bisa didapat setelah mereka lulus pelatihan higiene komprehensif dan tersertifikasi. Kedua, bentuk tim audit makanan interdisipliner yang terdiri dari ahli gizi, ahli sanitasi, dan ahli epidemiologi. Mereka harus berwenang melakukan inspeksi dadakan, tes cepat, serta verifikasi suhu dan waktu penyajian makanan. Ketiga, menerapkan "Aturan Besi" penyajian: makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak, dengan termometer menjadi perangkat wajib di setiap dapur.
Program MBG adalah komitmen moral dan politik bangsa. Namun, tanpa landasan keamanan pangan yang kokoh, tujuan mulianya tidak mungkin tercapai. Ribuan kasus keracunan adalah bukti bahwa fokus kita harus berubah dari sekedar kuantitas porsi ke kualitas dan setiap keamanan suapan. Pemerintah harus menerapkan prinsip “Nol Kecelakaan” dengan memuat pelatihan secara masif, menerapkan regulasi suhu dan waktu secara ketat, serta menjalankan pengawasan berbasis ilmiah. Inilah saatnya membuktikan bahwa kita mampu mengelola program besar dengan akuntabilitas penuh, bukan membuat ladang kelalaian. Sebab, yang dipertaruhkan di sini adalah masa depan Generasi Emas Indonesia, bukan sekadar angka di atas anggaran kertas.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
.png)
 21 hours ago
1
21 hours ago
1