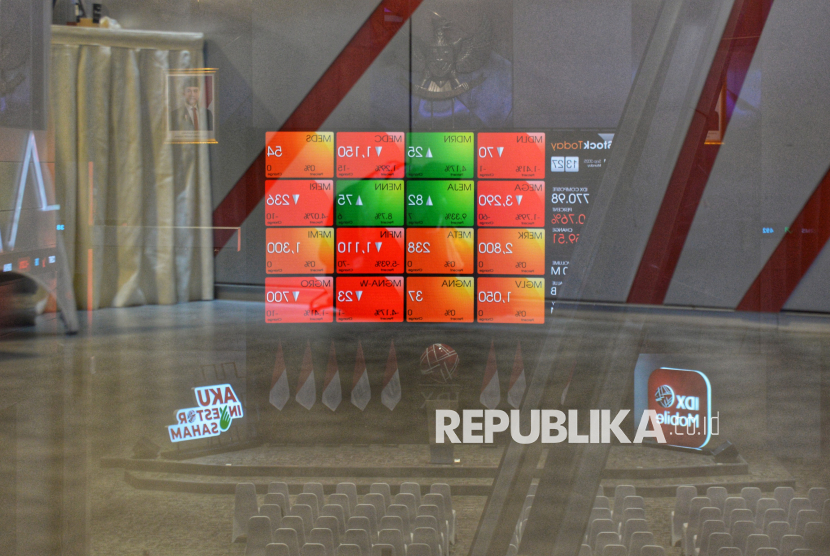Oleh: Edi Setiawan*)
Pendidikan bukan sekadar soal kurikulum dan gedung. Ia adalah denyut peradaban, tempat bangsa belajar menyalakan cahaya di tengah perubahan. Setelah satu dekade reformasi anggaran, pemerintah mencoba memulihkan makna dasar pendidikan: menghadirkan dampak nyata bagi anak, guru, dan masyarakat.
Sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI mencatat tujuh capaian melalui program Pendidikan Berdampak dengan total anggaran Rp181,72 triliun. Angka itu bukan semata soal serapan, tetapi ukuran seberapa jauh kebijakan mampu mengubah kehidupan.
Revitalisasi sekolah
Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi tonggak pertama. Dengan dana Rp16,97 triliun, pemerintah berhasil menghidupkan kembali 15.523 sekolah, melampaui target awal 10.440 unit. Di banyak daerah, ruang kelas yang dulu retak kini kembali ramai tawa anak-anak. Guru yang sempat kehilangan semangat kini percaya bahwa pengabdian mereka tak sia-sia.
Revitalisasi ini bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah simbol kehadiran negara. Bahwa setiap anak di pelosok berhak atas ruang belajar yang layak, cahaya lampu yang menyala, dan air bersih di halaman sekolahnya.
Namun, revitalisasi juga menantang pemerintah untuk menjaga keberlanjutan. Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi cara berpikir, bukan hanya cat ulang dinding. Di sinilah urgensi menciptakan sistem evaluasi berbasis hasil belajar (learning outcomes) agar setiap rupiah yang digelontorkan terukur dampaknya bagi murid, bukan sekadar laporan proyek.
Digitalisasi pendidikan
Melalui Instruksi Presiden No.7 Tahun 2025, pemerintah memperluas digitalisasi pendidikan untuk 285 ribu sekolah dari PAUD hingga SKB. Di Morotai, seorang guru kini bisa mengikuti pelatihan daring bersama rekan di Bandung. Anak-anak di Sumba dapat mengakses kelas virtual lintas pulau. Program ini bukan semata soal tablet dan jaringan, melainkan tentang kesetaraan kesempatan belajar. Digitalisasi menjadi jembatan antara keterbatasan dan cita-cita, antara daerah 3T dan pusat peradaban.
Namun, di balik semua kemajuan itu, tersisa jurang digital yang belum tertutup sepenuhnya. Banyak sekolah di pedalaman yang masih bergulat dengan sinyal lemah, listrik tak stabil, dan keterampilan digital guru yang terbatas. Jika digitalisasi tak disertai pendampingan dan literasi digital yang mendalam, ia bisa berubah menjadi kesenjangan baru: antara mereka yang terkoneksi dan yang tertinggal. Maka, tantangan sebenarnya bukan sekadar menyediakan gawai, tetapi memastikan transformasi digital menjadi transformasi sosial.
Kompetensi guru
Kualitas pendidikan bertumpu pada guru. Karena itu, pemerintah mengalokasikan Rp13,2 triliun untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Sebanyak 785 ribu guru non-ASN, 253 ribu guru PAUD nonformal, dan 804 ribu peserta PPG menerima tunjangan dan pelatihan karier. Tambahan insentif Rp300 ribu per bulan selama tujuh bulan sejak Juni 2025 menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
Ini bukan soal angka, tetapi pengakuan. Guru bukan pelengkap sistem, melainkan jantung dari seluruh perubahan. Namun, penghargaan finansial tanpa pembinaan berkelanjutan hanya menghasilkan kepuasan sesaat. Tantangan berikutnya adalah memperkuat ekosistem pengembangan profesi guru berbasis komunitas belajar, di mana guru saling bertukar praktik terbaik, menulis karya inovatif, dan membangun budaya reflektif.
Anak tetap di sekolah
Kemiskinan tak boleh menjadi alasan berhenti belajar. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebanyak 18,5 juta siswa menerima manfaat dari Rp13,5 triliun bantuan. Di wilayah terluar, 4.679 siswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) menerima dukungan Rp127 miliar.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, bantuan ini bukan sekadar uang sekolah—tetapi tiket menuju masa depan yang lebih baik. Negara hadir untuk memastikan setiap anak terus bermimpi, tanpa dibatasi dompet orang tuanya.
Namun, pendidikan yang benar-benar berdampak tak berhenti pada akses. Ia menuntut kualitas. Banyak penerima bantuan yang tetap menghadapi kendala belajar akibat minimnya literasi dasar. Maka, investasi sosial dalam pendidikan harus bergeser dari sekadar "mengirim anak ke sekolah" menjadi "menjamin anak benar-benar belajar."
BOSP sebagai oksigen pendidikan
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagaikan oksigen bagi sistem pendidikan. Ini menghidupi kegiatan belajar sehari-hari agar tak padam meski jauh dari pusat kebijakan.
Sebesar Rp59,3 triliun telah disalurkan untuk 50,4 juta siswa dan 422 ribu satuan pendidikan. Dana ini menjaga sekolah tetap hidup, terutama di wilayah terpencil yang jauh dari dukungan swasta.
Negara juga memperkuat penghormatan bagi guru ASN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai Rp70 triliun, mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,52 juta guru, Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332 ribu guru, dan Tunjangan Khusus (TKG) bagi 62 ribu guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Penanaman karakter
Di tengah derasnya arus digital, pendidikan karakter kembali ditegakkan melalui program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bersosialisasi, dan tidur cukup.
Anak belajar bukan dari ceramah, tetapi dari contoh. Maka, guru, orang tua, dan pemimpin lokal harus menjadi wajah nyata dari nilai yang diajarkan. Pendidikan karakter bukan sekadar program, tetapi proses kebudayaan.
Pendidikan yang membumi
Hasil survei Indostrategi Research and Consulting (Oktober 2025) menempatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebagai menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Capaian itu mengungguli sejumlah kementerian ekonomi dan infrastruktur—sebuah sinyal bahwa reformasi pendidikan kini menjadi salah satu wajah optimisme publik terhadap pemerintahan.
Namun, tingginya kepercayaan itu juga mengandung ujian. Publik menaruh harapan agar "pendidikan berdampak" tak berhenti sebagai jargon birokrasi.
Pendidikan berdampak bukan proyek jangka pendek, tapi proses menumbuhkan manusia yang utuh—yang berpikir kritis, berempati, dan berdaya.
Ketika sekolah menjadi ruang gembira, guru kembali dipercaya, dan anak-anak terus bermimpi, di situlah bangsa sedang bertumbuh. Membumikan pendidikan berarti menempatkannya kembali di hati rakyat: sederhana, dekat, dan berdaya.
*) Edi Setiawan adalah dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA.
.png)
 6 hours ago
3
6 hours ago
3